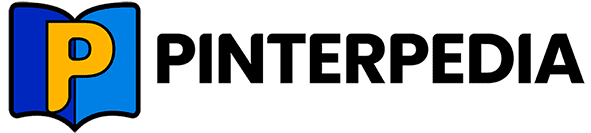khusus. Tapi masalahnya, ada saja orang sehat bugar yang pura-pura butuh prioritas. Ada yang ngaku pegal sedikit lalu merasa berhak nyelip. Ada juga yang pura-pura bingung lalu diarahkan ke jalur cepat.
Ketika jalur prioritas disalahgunakan, rasa percaya masyarakat ikut terkikis. Orang yang benar-benar butuh jadi terhalang karena ada yang lebih duluan “pura-pura butuh”. Akhirnya jalur prioritas malah dicurigai, bukan dihormati.
Kalau dibiarkan, fasilitas yang seharusnya jadi bentuk empati berubah jadi bahan olok-olok. Dan inilah yang membuat budaya antri di Indonesia terasa makin absurd.
5. Minimnya inovasi digital untuk mengurangi penumpukan
Di era ponsel pintar, mestinya sistem antrian sudah bisa lebih manusiawi. Banyak negara sudah pakai aplikasi untuk ambil nomor antrian, bahkan bisa pantau giliran lewat notifikasi. Jadi orang bisa menunggu di kafe terdekat atau di rumah sambil ngopi, lalu datang tepat waktu.
Sayangnya di Indonesia, sistem manual masih merajai. Orang harus berdiri berjam-jam, saling desak, saling lempar tatapan sinis. Padahal teknologi digital bisa jadi solusi sederhana untuk mengurangi penumpukan.
Bayangkan kalau rumah sakit atau kantor pelayanan publik pakai aplikasi antrian online yang benar-benar jalan. Warga tidak perlu datang subuh-subuh hanya untuk rebutan nomor. Energi bisa dipakai untuk hal lain, bukan habis di ruang tunggu yang sumpek.
Antrian di Indonesia sering kali jadi ujian kesabaran. Dari nomor antrian yang diabaikan, barisan yang melebar tanpa arah, titip tempat yang bikin gondok, jalur prioritas yang disalahgunakan, sampai sistem manual yang bikin orang berdiri lama-lama. Semua itu seakan menunjukkan bahwa kita masih sulit menghargai keteraturan.
Padahal antri bukan hanya masalah menunggu. Ia adalah simbol