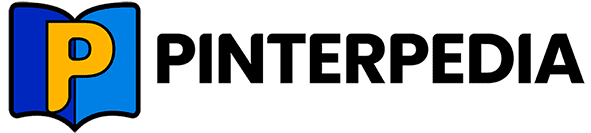sensasi internal, misalnya menghirup udara kaya karbon dioksida, dia bisa panik juga.
Artinya, ada jalur ketakutan lain di luar amigdala. Kalau amigdala mengurus ancaman eksternal, tubuh masih punya cara lain untuk merasa takut terhadap ancaman internal. Misalnya rasa sesak atau sinyal tubuh kekurangan oksigen. Jadi meskipun amigdala mati lampu, otak manusia bukan berarti benar-benar kehilangan semua jalur ketakutan.
Kasus ini bukan sekadar anekdot medis. Ia jadi pintu masuk untuk memahami cara otak bekerja. Selama ini kita sering menyamakan amigdala dengan pusat ketakutan. Tapi dari kasus Urbach Wiethe, ternyata sistemnya lebih kompleks. Ada jalur cadangan, ada percabangan. Otak ternyata tidak pernah mengandalkan satu pintu saja untuk sesuatu yang vital seperti bertahan hidup.
Lebih jauh, studi ini bikin para peneliti berpikir ulang tentang cara mengobati gangguan yang berhubungan dengan ketakutan berlebihan. PTSD misalnya, di mana penderita dihantui kenangan menakutkan yang tak kunjung reda. Kalau jalur ketakutan bisa dipahami dengan lebih detail, siapa tahu suatu hari kita bisa menekan tombol yang tepat untuk meredakan penderitaan itu.
Ketakutan Merupakan Bagian Identitas Manusia
Yang menarik, fenomena ini juga mengguncang cara kita melihat diri sendiri. Takut itu sering dianggap kelemahan. Kita diajari sejak kecil untuk berani, untuk menghadapi ketakutan. Tapi ironisnya, justru rasa takut itulah yang memastikan kita tetap bisa tumbuh sampai dewasa. Tanpa takut, banyak keputusan hidup mungkin berakhir tragis.
S. M. sendiri hidup dengan realitas unik. Dia nggak gentar menghadapi hal-hal yang bikin orang lain mundur, tapi di sisi lain dia juga lebih rawan bahaya. Inilah wajah paradoks manusia: bahkan kelemahan yang kita